Review Identitas Politik Pak Kunto (3)
“Makin demokratis suatu sistem, makin menguntungkan Islam,” yakin Kuntowijoyo. Menurutnya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan rakyat. Bentuk kekuasaan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi segenap warga negara.
Kuntowijoyo, dengan merujuk dua sumber utama hukum Islam, menyusun kaidah-kaidah demokrasi. Pertama, ta’aruf (saling mengenal). Dalam surat Al-Hujurat: 13, terdapat ungkapan bahwa tujuan pengelompokan manusia, yang berlatar beda, adalah ta’aruf, saling mengenal. Saling mengerti kepentingan satu sama lain, sehingga hak-hak antarsesama tidak dilanggar.Ta’aruf mensyaratkan persamaan dan kebebasan. Tidak ada warga yang dinomorsekiankan, apa pun suku dan agama yang melekat. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Hak-hak terselenggara tidak monologis kelompok mayoritas. Tidak anarkis baik oleh birokrasi maupun kelompok masyarakat.
Kedua, syura (musyawarah). Dalam surat Asy-Syura: 38, “… dan orang-orang yang aturannya [dalam semua urusan yang menyangkut kepentingan Bersama] adalah musyawarah di antara mereka, ….” Juga dalam surat Ali Imran: 159, “… Dan, bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, ….”
Muhammad Asad, dalam The Message of the Quran, menjelaskan bahwa pemerintahan melalui mufakat dan dewan itu sebagai klausul fundamental dari seluruh hukum Al-Quran tentang kenegaraan.
Dalam praktik yang ditelandankan Nabi Saw. pun betapa beliau sangat menghargai musyawarah. Nabi Muhammad Saw. menyelenggarakan musyawarah jelang Perang Uhud. Sang nabi berpendapat bahwa lebih baik bertahan dalam kota, tapi mayoritas sahabat menghendaki berperang di luar kota. Dan, Nabi Saw. mengalah kepada kehendak mayoritas, meski akhirnya, kita tahu dalam perang di Bukit Uhud itu kaum muslim mengalami kekalahan. Banyak jatuh korban di tubuh umat Islam, termasuk Nabi Muhammad Saw. terluka. Itu berarti, dalam musyawarah proses lebih penting dari hasil.
Ketiga, ta’awun (kerja sama). Dalam surat Al-Maidah: 2, “… dan tolong-menolonglah dalam menyuburkan kebajikan dan kesadaran akan Allah, dan janganlah tolong-menolong dalam neyuburkan kejahatan dan permusuhan; dan tetaplah sadar akan Allah ….”
Kuntowijoyo mencatat ada dua kepentingan yang meniscayakan kerja sama: kepentingan manusia dan “kepentingan” Tuhan. Dan, kepentingan itu menemu titik temu pada kepentingan ekonomi.
Dalam surat Ali Imran: 92, “[Adapun kalian, wahai orang-orang beriman,] tidak akan pernah kalian meraih kesalehan sejati, kecuali kalian menafkahkan sebagian dari apa yang kalian sendiri cintai untuk orang lain; dan apa pun yang kalian nafkahkan—sungguh, Allah Maha Mengetahuinya.”
Ukuran kebajikan sosial, betapa iman seseorang belum sempurna jika iman itu tak membuatnya sadar akan kebutuhan material.
Keempat, mashlahah (menguntungkan masyarakat). Dalam hal ini, Pak Kunto tampak ingin menekankan bahwa agama, sebagai moral force, tidak sebatas bersifat individual dan hanya melalui kebudayaan. Agama dapat berpengaruh dalam struktur dan proses berbangsa serta bernegara, termasuk dalam demokratisasi, melalui objektivikasi. (Tentang objektivikasi bisa dibaca di review yang kedua).
Kuntowijoyo mengetengahkan “kesalahan” umat Islam, yang memandang masalah politik sebagai masalah sederhana, bahwa asal semua berbuat baik, selesai urusan. Padahal, baik menurut siapa? Karena “baik” seorang majikan berbeda dengan “baik” seorang buruh. Pengusaha berbeda dengan masyarakat bawah. Politisi berbeda dengan petani. Dan, demokratisasi jelas mensyaratkan kriteria kebajikan itu berkait dengan mayoritas, dengan kepentingan umum. Maka, mashlahah bukan hanya untuk dan milik elite, bukan hanya milik segelintir kaum the have.
Kelima, ‘adl (adil). Dalam surat An-Nisa: 58, “Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Selanjutnya, surat Al-An’am: 152, “Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu.”
Untuk kebutuhan demokrasi, Kuntowijoyo mengemukakan dua macam keadilan: distributive justice (demokrasi sosial) dan productive justice (demokrasi ekonomi). Pelaku keadilan distribusi adalah negara, dan penerimanya semua warga negara. Bentuknya bisa bermacam-macam jaminan sosial. Sementara pelaku keadilan produksi adalah perusahaan, dan penerimanya karyawan, serta bentuknya berupa pembagian pemilikan kekayaan.
Keenam, taghyir (perubahan). Perubahan keadaan sangat ditentukan oleh peranan manusia yang berkesadaran. “Sungguh, Allah tidak mengubah keadaan manusia, kecuali mereka mengubah lubuk diri mereka sendiri.” (Ar-Ra’d: 11).
Muhammad Asad menjelaskan ayat itu, sebagai gambaran hukum sebab-akibat yang ditetapkan Allah (sunnatullah), yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Sehingga, kebangkitan dan keruntuhan suatu peradaban akan bergantung pada kualitas moral umatnya dan pada perubahan dalam “lubuk diri mereka” sendiri.
Sehingga jelas bahwa demokrasi, selain sebagai teori kekuasaan, adalah teori tentang hak-hak rakyat. Dan dalam sistem kekuasaan kita mengenal dua hal: birokrasi dan kepemimpinan.
Birokrasi yang diperlukan adalah yang legal-rasional. Birokrasi yang pengangkatannya berdasar kualifikasi teknis yang objektif. Birokrasi yang melayani kepentingan umum, bukan kepentingan pengusaha semata. Berikutnya, kepemimpinan yang dibutuhkan juga yang bersifat legal-rasional, bukan yang kharismatis.
Namun, perjalanan demokrasi kita tidak berjalan mulus. Ada masyarakat yang masih hidup di tingkat praagraris, sebagian besar berada dii tingkat agraris, dan hanya sedikit yang telah menikmati kue kemajuan.
Di sana sini masih banyak sisa-sisa feudalisme. Sistem politik masih lebih menguntungkan kekuasaan ketimbang masyarakat. Tingkat melek pengetahuan masyarakat masih rendah, budaya lisan (terlebih kini pada era media sosial) masih merajai.
Kuntowijoyo menawarkan, pertama, elite agama—yang memang potensial menjadi vote getter—harus mengambil jarak dengan semua partai politik. Partisipasi elite agama dalam berpolitik bersifat pragmatis, tidak praktis.
Kedua, kepada birokrasilah andalan kita, bukan kepemimpinan. Birokrasi ibarat pabrik, maka stabilitas kolektif segenap anak bangsa lebih diutamakan, ketimbang segelintir elite politik dan elite ekonomi.
Ketiga, umat Islam harus tegas merumuskan musuh bersama, yakni sekularisme. Sekularisme, berasal dari kata secular, seculer, seculere berarti temporal, sebagai paham yang mencoba memisahkan urusan luar-dunia dari dunia ini. Dan, ada dua macam sekularisme: sekularisme objektif dan sekularisme subjektif.
Sekularisme objektif terjadi bila secara struktural terdapat pemisahan antara agama dengan yang lain. Sedangkan sekularisme subjektif terjadi bila pengalaman sehari-hari tidak dapat lagi dipetakan dalam agama, ada pemisahan antara pengalaman hidup dengan pengalaman keagamaan.
Contoh riil sekularisme objektif tampak di Turki yang terang-terangan memisahkan antara negara dan agama. Kemal Ataturk (1881-1938) menghilangkan pengaruh ulama dan pemimpin tarekat pada negara. Sementara selarisme subjektif bisa terjadi pada siapa saja. Kuntowijoyo mengilustrasikan bagaimana sekularisasi terjadi pada seorang ilmuwan. Karena memang ilmu yang dari asalnya semata-mata rasional dan objektif, maka pengalaman keagamaan sehari-hari berpotensi tidak menunjang kegiatan berilmu.
Sebagai misal, dalam laboratorium fisika, hasil yang diperoleh oleh peneliti muslim dengan peneliti yang tak beragama, sama saja. Hasil objektifnya sama. Oleh karenanya, rumusan objektivikasi menjadi relevan untuk mengatasi persoalan sekularisme subjektif (juga sekularisme objektif). Bahwa nilai keagamaan itu tidak pada hasil, tidak di ujung, tapi pada proses, pada niat. Peneliti sekular mengadakan subjektivikasi terhadap pengalamannya, sementara peneliti muslim mengadakan internalisasi.
Begitu.
Ungaran, 14/11/2021

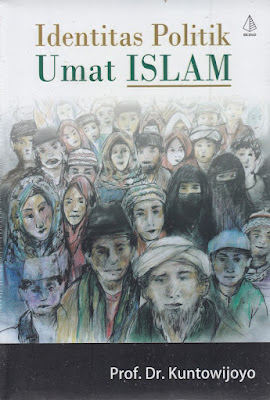





0 Comments