Semalam terlalu sedikit tidurku. Bahkan nyaris tak tidur. Pukul 04.30 baru bisa merebahkan badan di atas kasur. Tak aneh, pukul 09.00 aku baru bisa membuka mata, meski masih bergolek di kamar tidur. Itu pun karena dibangunkan Rahma untuk sarapan pagi. Anak-anak sudah berangkat sekolah.
“Maafin Ayah ya, Bun! Ayah bangun kesiangan, sehingga tak sempat mengantar anak-anak ke sekolah,” ucapku sambil berjalan ke meja makan.Istriku itu sudah menunggu untuk makan bersama. Aku mencium aroma khas kopi yang mengundang selera. Aku lihat nasi putih terhidang dalam mangkuk besar. Sayuran rebus tanpa kuah di atas piring dan di sebelahnya satu mangkuk kecil sambal pecel. Beberapa helai daun kemangi di atas piring kecil. Ada pula tempe mendoan dan telur dadar kesukaanku. Terakhir, rempeyek yang masih terbungkus plastik, jelas ini baru saja dibeli.
“Wow kopi rempah!” teriakku sembari menyeruput sedikit kopi setelah meletakkan pantatku di atas kursi. Duduk menghadap piring kosong dengan sendok di atasnya, berhadapan dengan istri.
“Tadi Bunda yang antar anak-anak ke sekolah,” Rahma buka suara.
"Don't worry, Honey. Besok-besok, tak cuma anak-anak. Dirimu pun kan kuantar keliling kampung."
"Kok hanya keliling kampung?"
"Ya wis ke mana?"
"Udah ah! Paling cuma obral janji!
Istriku mengambilkan nasi putih, sayuran rebus, dan kemangi ke atas piring. Dia siram dengan sambal pecel, kemudian ia sodorkan kepadaku. Ia ambil bungkusan plastik isi rempeyek dan menggunting pucuknya.
“Rempeyek, Yah!” Ia taruh di atas piringku. Hal yang sama ia lakukan di atas piringnya. Kemudian sama-sama makan. Sarapan pagi tanpa gaduh anak-anak.
“Bagaimana pecelnya, Yah?”
“Enak! Tidak seperti biasa. Coba resep baru nih? Rempeyek ini juga gurih.”
“Ya, pasti enaklah. Kan Bunda beli di warung pojok Pasar Ungaran.”
“Oalah beli! Ayah kira Bunda yang masak. Namun serius, enak banget.”
“Ya, Bunda hanya masak nasi putih dan air pagi ini. Habis Ayah juga bangun siang. Kan Bunda kudu antar anak-anak sekolah. Nah, habis dari sekolah, Bunda sekalian mampir pasar.”
“Ya, ya, ya, maafin Ayah, yang bangun kesiangan! Oh iya, Bunda kenal pemilik warung yang jual pecel ini kan?”
“Kenal! Emang kenapa?”
“Ya, kenapa tidak sejak dulu langganan pecel dari dia? Kan enak sarapan pagi dengan menu istimewa kayak begini.”
“Ah, dasar hamba perut! He-he....” Rahma tertawa meledek. “Ya, Bunda juga baru kenal tadi pagi kok, Yah. Itu pun semula iseng. Tak sengaja melihat warung kecil tetapi dikerubuti antrean pembeli.”
“Pemilik warung itu,” sambung Rahma, “pasangan muda suami-istri. Ya, seumuran kitalah. Beda tipis. Mereka urban dari Blora. Baru tiga tahun ini mengadu nasib di kota kecil kita ini. Anak mereka baru satu, perempuan, dan kini duduk di kelas VI SD Negeri Induk Ungaran. Mereka tinggal di rumah kontrakan dekat pasar, persisnya di gang sempit belakang Bank Perkreditan, samping rumah makan padang.”
“Oh ya, Ayah kenal daerah itu. Terus warung pecel yang mereka tempati sebelah mana?”
“Sabar, Yang, Sayangku! Pelan-pelan, nanti keselek dan nasinya tumpah ke lantai. He-he....” lagi-lagi istriku meledek. Kemudian ia melanjutkan cerita. “Mereka sewa kios di pojok timur-utara, ya deretan kios-kios bagian luar Pasar Ungaran yang memang disewakan untuk warung makan dan toko kelontong. Mereka buka warung makan sederhana yang menjajakan: tahu campur, sambal pecel, dan ketoprak. Menu selingan sayur pepaya muda, oseng-oseng daun singkong, kacang panjang, oseng tahu tempe, orak-arik sayur, tempe dan tahu mendoan, serta telur dadar. Oh ya nama mereka Mas Topo dan Mbak Tini, Martini lengkapnya. Namun orang-orang pasar kerap memanggil Mbak Tini. Menu minuman yang mereka tawarkan hanya teh, jahe, dan kopi.”
“Dan air putih tentu saja.” Aku potong paparan istri sembari menambah nasi dan menuang sambal pecel ke atas piringku. Aku coba pula telur dadar yang menganggur belum terjamah. Memang istriku tak doyan telur dadar. Dan, aku yakin tiga lapis telur dadar itu ia sengaja untuk aku dan sang sulung. Lantaran si bungsu juga tidak gemar telur.
“Ya, air putih. Mereka sajikan dalam kendi. Jadi minum air putihnya gratis.”
“Kok aneh? Hari gini masih ada yang pamer kendi.”
“Itulah yang bikin Bunda penasaran dengan Mas Topo dan Mbak Tini. Maka Bunda berlama-lama nongkrong di sana. Bunda jajal tahu campur mereka. Dan, ini yang tak wajar, saat Bunda minta air putih kemasan, mereka geleng kepala. Ternyata mereka tak menyediakan botol air kemasan. Mas Topo mengulurkan gelas dan minta Bunda tuang air putih dari kendi yang mereka taruh di tengah meja. Ya, di atas meja itu ada tiga kendi ukuran sama yang sama-sama berisi penuh air putih.”
Aku tertegun menyimak paparan Rahma. Sesaat aku pun istirahat mengunyah. Takjub, terlebih riasan Rahma yang apa adanya pada pagi ini sungguh bikin merak hati.
“Lantas Bunda tanya ke Mas Topo, kenapa tidak sedia botol kemasan yang menurut pendapat Bunda lebih sehat ketimbang air dalam kendi? Bunda tak menyangka atas jawaban Mas Topo, yang mengatakan justru air dalam kendi itulah yang lebih menyehatkan ketimbang bikinan pabrik, dan bla bla.... Banyak sekali uraian Mas Topo tentang pabrik, korporasi modal, dan kedaulatan air. Coba Ayah bayangkan betapa malu Bunda tadi pagi yang salah persepsi dan dikuliahi seorang penjual di warung makan. Untung, pembeli yang lain sudah tak mengantre. Tinggal Bunda dan seorang bapak tua bersama anak kecil, entah cucu atau anaknya, Bunda tak tahu. Dan satu hal lagi yang sungguh-sungguh menarik, Mas Topo sempat diminta jadi tim sukses Pak Jono….”
“Lukas Jono!” aku sela uraiannya.
“Tepat! Sang caleg DPR RI dari Partai Padi itu. Namun, Mas Topo menolak. Ia takut konsekuensinya. Ia nggak mau terlibat politik obral uang. Ia tidak mau turut melestarikan tradisi umbar janji dan memberi uang bagi pemilih. Bahkan ia tolak tawaran Pak Jono yang mau membikinkan rumah sederhana untuknya. Konyol kan? Padahal, hari gini ketimbang terus-terusan jadi kontraktor, ngontrak rumah sana sini, mending bernaung di rumah sendiri ta! Pikir Bunda, tawaran rumah itu nanti, selain untuk tempat tinggal, bisa buat melangsungkan usaha warung makan mereka. Namun, sekali lagi Mas Topo dan Mbak Tini menolak uluran Pak Jono. Alasan mereka, hidup cuma sesaat kudu bersih dari praktik money politics. Gimana tuh, Yah, keren kan!”
Mendengar paparan Rahma, aku tak sanggup menghapus rasa penasaran atas sosok Mas Topo dan istrinya, Mbak Tini. Mereka bak dongeng, yang terus mengiang di telingaku. Korporasi, kedaulatan air, pemodal, dan pabrik kerap kudengar dalam diskusi-diskusi bersama teman-teman seangkatan kuliahku dulu. Namun, berjarak dari rayahan obral uang di masa kampanye, sungguh teramat sangat istimewa. Mas Topo, termasuk jenis langka, lantaran tak sedikit yang kepincut, menjadikan obral uang sebagai jalan hidup. Apalagi di tengah krisis macam hari ini. Uang jadi segalanya. Sehingga, lazimlah bahwa seolah yang berhak duduk di kursi legislatif (juga eksekutif) adalah orang-orang yang berduit, walau minus kemampuan, dan tanpa integritas. Minim keberpihakan pada rakyat. Uang sedemikian rupa telah jadi senjata ampuh untuk memuluskan seorang kandidat menduduki kursi sebagai anggota dewan atau kepala daerah. Hmmm, aku harus ketemu Mas Topo. Ia harus menjelaskan kenapa begitu getol menolak jadi tim sukses? Kenapa menolak dibangunkan rumah? Sedemikian mengerikankah money politics itu? Dan pula, pilihan dia atas kendi, sekadar gaya-gayaan, atau memang bagian dari perlawanannya terhadap serangan politik uang?
Ah, tiga tahun ia telah mengontrak rumah di Ungaran. Ia berasal dari Blora, dan sontak tebersit: adakah hubungan kekerabatan antara Mas Topo dengan pengarang realis terkenal, Pramoedya? Yang aku tahu, Pramoedya Ananta Toer sedemikian tegas menolak kuasa uang. Pramoedya dalam tulisan-tulisannya bertutur tentang kekuasaan uang yang benar-benar memorat-maritkan kehidupan masyarakat bawah. Dan, Mas Topo! Siapa dia? Kenapa pula ia bersama istrinya seakan meneguhkan diri sebagai pegiat antipolitik-uang? Bahkan menu makan dan minum yang mereka sajikan, seolah mencerminkan usaha meneguhkan kedaulatan makanan khas lokal. Tahu campur, sambal pecel, dan oseng-oseng tak lain merupakan produk menu lokal yang hanya dijajakan di warung-warung sederhana dengan hasil pendapatan yang juga sedikit. Lagi-lagi Mas Topo dan istrinya berani buka warung sederhana.
“Heran kan?”
“Ya, Bun. Ayah tergoda oleh cerita Bunda. Menurut pendapat Ayah, Mas Topo dan istrinya itu sedang melakoni hidup sebagai pejuang antikerakusan. Mereka rela hidup pas-pasan dengan usaha sederhana pula.”
“Iya sederhana, tapi berkarakter, Yah. Warung mereka kecil, tetapi menu yang mereka hidangkan menu sehat yang seakan mengingatkan kita agar berani mengambil jarak dari segala yang berbau kemaruk dan aneka rupa kemasan pabrik besar.”
“Baiklah. Bagaimana kalau besok atau nanti sore kita ajak anak-anak ke warung Mas Topo?”
“Besok saja. Sekalian jalan-jalan pagi. Kan Sabtu, anak-anak libur. Bagaimana? Oh ya, mau tambah sambal pecel?” Rahma menyorongkan mangkuk berisi sambal pecel kepadaku.
“Sudah, Bun. Perut Ayah sudah tak berkeruyuk lagi. Baiklah, besok pagi saja kita ke Mas Topo.”
Istriku membereskan piring dan gelas kotor ke tempat cucian. Kemudian menutup sisa nasi, sayuran, tempe, dan sambal pecel dengan tutup makanan. Lalu, kami beranjak ke ruangan depan.
***
Anak-anak bangun pagi. Mereka riang, karena semalam Rahma memberi tahu pagi ini akan mengajak jalan-jalan. Mereka sudah mandi dan kini bermain di halaman rumah, sembari menunggu persiapanku dan istri. Sengaja Rahma tidak masak hari ini. Bahkan masak air pun tidak, apalagi nasi dan sayuran. Hari ini kami berencana sarapan pagi di warung pecel Mas Topo. Tas kecil berisi uang, HP, pensil, dan buku catatan sudah kuselempang ke pundakku. Ya, hari ini aku bawa buku catatan. Aku ingin mengorek dan mencatat keterangan sebanyak mungkin dari lisan Mas Topo. Siapa gerangan sesungguhnya ia? Apa motivasinya buka warung di tengah gaya hidup yang serba siap saji ala pabrik modern?“Ayah! Ada asap dari arah timur!” teriak Isa. Anak sulungku itu lari tergopoh masuk rumah dan lantas menarik tanganku ke luar rumah.
Benar. Asap hitam disusul api berkobar membubung tinggi ke udara. Rumah siapa yang terbakar? “Oh tidak!” jeritku. Asap hitam itu mengepul persis di atas Pasar Ungaran. Jangan, jangan, ya, lantas aku masuk ke dalam rumah, cepat-cepat ajak istri ke luar.
“Bun, pasar terbakar!”
“Hah?” Rahma melongo tak percaya. “Terus bagaimana dengan Mas Topo, Mbak Tini, dan warung mereka?”
“Ya, Ayah juga belum tahu. Maka Ayah ingin ajak Bunda ke sana sekarang.”
“Ayah sendiri saja ke sana! Biar cepat.”
“Ayah kan belum tahu persis warung Mas Topo. Ayah juga belum paham rupa wajah Mas Topo dan Mbak Tini. Sudah! Bunda harus ikut, sekalian anak-anak kita ajak!”
***
Sepeda butut milik kami membelah Jalan Pattimura. Jalanan ramai. Orang-orang tumpah ruah naik sepeda motor dengan tujuan yang sama: Pasar Ungaran. Saking ramai pengguna jalan, biasanya sepuluh menit tiba di pasar, kini lebih. Benar saja. Arus di Jalan Gatot Subroto macet. Bus-bus besar antarprovinsi berhenti.“Ah! Bisa-bisa setengah jam baru sampai pasar, Bun. Arus macet begini.”
“Ayah, itu apinya sudah tak setinggi tadi!” anak sulungku menimpali.
Benar, kulihat api tak membubung tinggi. Tinggal asap yang menghitam. Berarti pemadam kebakaran sudah berhasil menjinakkan api yang mengganas. Hmmm, bagaimana dengan Mas Topo? Aku bertanya-tanya kembali dalam hati, seraya mendremimilkan doa agar warung Mas Topo tak apa-apa. Mas Topo, Mbak Tini, dan putri semata wayang mereka selamat dari kobaran api.
Injak pedal kuat-kuat dan jalan berkelak-kelok, aku terjang kemacetan. Di tengah bising suara klakson serta sirine pemadam kebakaran, benar dugaanku, setengah jam baru bisa mendekati pasar. Jarak seratus meter dari pasar, kami berdiri di samping kerumunan orang. Lagi-lagi kami hanya sanggup menatap sedih, menyaksikan ibu-ibu pedagang di pasar panik mengangkuti barang-barang. Sementara pasar sudah ludes. Tinggal menyisakan tembok hitam tak beratap serta asap menghitam. Mas Topo, istri, dan putrinya? Entahlah....
Ungaran, 18/11/2019
Baca juga: Sekali waktu naik Bus

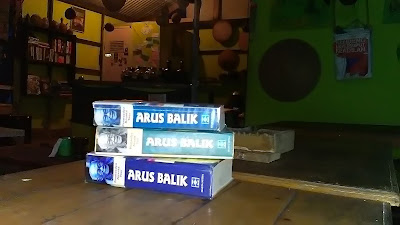





0 Comments